Ekologis Cahyono
Peneliti/Aktif Sajogyo Institute
Mahasiswa PhD Sosiologi Pedesaan IPB
Pemberian konsesi pertambangan oleh pemerintah kepada organisasi keagamaan telah memicu kritik. Sebab, mereka khawatir kebijakan tersebut justru akan berlanjut dan memperburuk krisis sosial ekologi dan pertanian akibat rezim pengerukan tambang. Sejauh ini, masih sulit menemukan praktik industri ekstraktif di tanah air yang menghormati kemanusiaan, keadilan, dan kelestarian ekologi. Sebaliknya marginalisasi, eksklusi, praktik korupsi, pencemaran (air dan udara), perampasan tanah, konflik pertanian, pengrusakan. Sebagian besar habitat manusia justru sering terlihat mendominasi (TII 2024, Jatam 2024).
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penerapan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara, Pasal 83A mengartikan Ormas keagamaan menjadi prioritas hukum bagi yang memiliki izin beroperasi. Sebab, dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) bisa ditawarkan terutama kepada organisasi komersial milik ormas keagamaan.
Menurut Pasal 83A ayat (2), WIUPK yang dapat dikelola oleh badan usaha organisasi massa keagamaan adalah wilayah pertambangan batubara yang telah beroperasi atau mulai berproduksi. Pasalnya, pemerintah mengevaluasi izin usaha pertambangan yang diterbitkan swasta sejak tahun 2022 dan mengidentifikasi sekitar 2.078 izin usaha pertambangan (IUP) yang dinilai belum melaksanakan rencana bisnisnya dengan baik. Organisasi keagamaan dapat memperoleh izin usaha ini.
Di luar perdebatan mengenai apakah sebuah organisasi keagamaan dapat mengelola industri pertambangan dengan baik, mungkin penting untuk mempertimbangkan secara serius mengapa praktik keagamaan bisa bersifat dua sisi. Di satu sisi, semua agama yang memiliki organisasi keagamaan tentu mempunyai argumentasi bahwa merekalah pembela utama dalam menjaga alam, membela keadilan dan kemanusiaan. Namun di sisi lain, mengapa mereka justru menjadi pendukung bahkan melegitimasi, atas nama agama, praktik buruk kebijakan pembangunan yang sekaligus merusak alam dan mengabaikan keadilan dan kemanusiaan?
Hasil kajian pertama bertajuk “Agama dan Perkembangan Tokoh Ganda Agama dalam 10 Potret Kasus di Indonesia” yang dilakukan ICRS-UGM dan Sajogyo Institute (2020) jelas menunjukkan praktik baik dan buruk yang mengatasnamakan agama. Misalnya saja penolakan Gereja Katolik terhadap ranjau di Manggarai (2009). Para pemimpin Gereja Katolik mengorganisir komunitas tersebut untuk menuntut diakhirinya operasi penambangan perusahaan. Hal ini disusul dengan pernyataan Uskup Lenteng bahwa Keuskupan Ruteng adalah gereja anti tambang (2014).
Pada tahun 2018, terbentuklah Ikatan Masyarakat Adat (Imamat) Anti Tambang Manggarai yang mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang peduli terhadap persoalan pertambangan. Contoh lainnya adalah penolakan Pendanda Hindu Bali bersama ForBali terhadap Kominte Teluk Banoa (2016). Berdasarkan keputusan Pandhita Sabha, pedanda mengklaim terdapat situs suci di sekitar Teluk Banoa di kawasan Kominte yang masih digunakan umat Hindu untuk melakukan ritual keagamaan.
Contoh lainnya adalah warga Nahdatul Ulama Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang didukung Front Nahdiyin Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) melawan PT Semen Indonesia dengan menggelar istigot besar-besaran di Pondok Pesantren Roudlout Tholibin di KH Mustofa Bisri (2015). Sebab selain menimbulkan konflik pertanian, Gunung Kendeng juga mengancam ekosistem karst dan penghidupan masyarakat disekitarnya, sehingga kerugian (dampak buruk, bahaya, kerusakan atau bencana) dianggap lebih besar dibandingkan manfaat (manfaat). atau kebaikan).
Namun yang menarik adalah dalam ketiga kasus tersebut, kelompok Gereja/Pendeta, Pendanda dan Ulama/Kyai di wilayah yang sama menggunakan argumentasi dan usulan keagamaan untuk secara langsung atau tidak langsung mendukung proyek pertambangan dan reklamasi tersebut. .
Kisah-kisah dalam tiga kasus di atas hanyalah ‘puncak gunung es’ dari kasus serupa lainnya; kasus-kasus ini mungkin tidak terungkap/terungkap dan kemungkinan besar lebih umum dan beragam di Indonesia. Tentu saja sikap keagamaan juga bersifat dinamis, berubah-ubah, dulu dan sekarang, dari yang tadinya menolak, terkadang mendukung. Namun, praktik agama bermuka dua tampaknya bukan merupakan ekspresi keagamaan yang spesifik pada satu agama.
Hampir semua agama mempunyai potensi yang sama, satu sisi bisa menjadi berkah, sisi lain bisa menjadi bencana bagi kehidupan manusia dan alam. Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan agama menjadi bencana: kemerosotan nilai dan penafsiran mutlak atas kebenaran agama, serta praktik politisasi dan instrumentalisasi agama.
Jika kita memikirkan dan mereaksikan gagasan Charles Kimball (2013), terlihat kapan agama bisa menjadi bencana? Dalam kasus teroris dan radikal, dengan berkedok agama, mereka secara sepihak menafsirkan teks-teks suci sesuai dengan ‘ideologi’ yang mereka yakini dan menciptakan ‘kebenaran suci’ yang tidak dapat disangkal. Pada titik ini agama sudah korup/dekaden.
Keruntuhan agama setidaknya bisa dilihat dari beberapa tandanya: Pertama, ketika suatu agama mengklaim kebenaran agamanya sebagai kebenaran tunggal dan mutlak. Kedua, adanya ketaatan buta terhadap pemimpin agama. Ketiga, agama menjadi terobsesi dengan kerinduan akan usia ideal, kemudian bertekad untuk membawa usia tersebut ke usia sekarang. Keempat, agama mengizinkan dan melegitimasi tujuan untuk menghalalkan segala cara. Kelima, adanya seruan perang suci untuk mencapai tujuan mereka.
Oleh karena itu, hal pertama yang membuat agama menjadi bencana adalah hancurnya nilai-nilai agama ketika mereka mengampuni kebenaran hasil penafsiran kitab-kitab suci, dengan alasan yang sangat bertentangan dengan perintah Yang Maha Kuasa. Agama bagi manusia dan alam yang diciptakannya. Dalam kisah tiga kasus di atas, yang menjadi landasan semangat perjuangan atas nama agama, baik yang menolak maupun yang mendukung, pada agama Kristen, Hindu, dan Islam, keduanya bermula dari kompilasi argumentasi interpretatif tentang doktrin dan nilai. . . diambil dari kitab suci agamanya masing-masing.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sumber permasalahan agama, baik bencana maupun anugerah, ditentukan pada poin di atas, yaitu ‘model dan bentuk penafsiran teks ajaran agama dalam kitab suci’, dan akhirnya sampai di situ. dasar dari keyakinan ini. ‘kebenaran mutlak’.
Sebaliknya, ketika upaya penghancuran agama akibat salah tafsir dan monopolisasi absolut dan buta atas keakuratan penafsiran tersebut dihindari, maka agama akan menjadi anugerah. Oleh karena itu, diperlukan bentuk penafsiran keagamaan yang lebih inklusif, manusiawi dan ekologis, sejalan dengan misi bahwa nilai dasar universal semua agama adalah rahmat bagi alam semesta.
Absolutisme dan absolutisme serta satu-satunya kebenaran dalam ‘penafsiran agama’ harus dihindari. Sebab, sebagai orang beragama, ia dibatasi oleh batas-batas imanensinya untuk mencapai kebenaran ketuhanan yang serba transenden (tidak terbatas). Dengan kata lain, ‘penafsir’ agama tidak boleh mengklaim memiliki lebih banyak ‘kebenaran absolut tentang/dari Tuhan’ dibandingkan yang lain.
Secara historis, agama hidup dan dihidupi oleh para pemeluknya yang senantiasa membangun kebudayaan dalam segala aspek kehidupannya, baik sosial, ekonomi, ekologi, dan politik, selaras dengan tantangan ruang-waktu zamannya. Dengan demikian terjadilah dialog, ‘akulturasi’ dan interaksi timbal balik antara nilai-nilai sakral dan universal (kemanusiaan, persaudaraan, kasih sayang, menjaga alam, dan lain-lain) dan nilai-nilai kemanusiaan duniawi (kekuasaan, kebutuhan, kesenangan tanpa batas [materialisme-hedonisme ). ). ], maksimalisasi keuntungan [kapitalis], dll.).
Yang dikhawatirkan, hal ini sering terjadi ketika ada hubungan antar umat beragama dan keinginan untuk mengumpulkan keuntungan – kekuatan politik yang menggunakan legitimasi agama. Jadi, hal kedua yang bisa membuat agama menjadi bencana adalah politisasi dan instrumentalisasi agama. Sebab praktik-praktik tersebut mempunyai dampak yang sangat merusak terhadap nilai-nilai universal agama.
Pertama, agama adalah tentang perdamaian, belas kasihan, kemanusiaan, perlindungan alam, dll. Ia akan kehilangan identitasnya sebagai sumber nilai sakral dan universal. Sebab dalam praktik perjuangan politik, segala cara dapat digunakan untuk mencapai tujuan perebutan kekuasaan. Tidak ada teman atau musuh yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan kekuasaan yang abadi. Solidaritas dukungan konstituen politik dibangun dan diperluas melalui instrumentalisasi agama sebagai alat politik, seringkali dengan perasaan fanatisme, merampas kedalaman makna dan interpretasi agama, menjadikannya lebih sekuler dan radikal.
Kedua, agama akan mengambil karakter yang lebih ekstrim dan tidak memiliki semangat moderasi. Sebab, agama diposisikan hanya sebagai alat dan komoditas politik demi kekuasaan pribadi dan kelompok. Oleh karena itu, ekspresi keagamaan yang akan muncul adalah kebijakan pemisahan ekstrim antara kawan dan musuh. Istilah agama sering disebut-sebut dengan santai sebagai pembenaran: sesat, murtad, munafik, sesat, dan sebagainya. menyukai. Faktanya, suatu istilah yang memiliki lebih dari satu penafsiran mempunyai monopoli dalam mendefinisikan kebenaran hanya menurut orang yang mengucapkannya.
Ketiga, agama akan kehilangan identitasnya sebagai entitas yang mampu menjalin persaudaraan antar umat beragama. Sebab ketika agama menjadi instrumen kekuasaan politik, maka ia akan menjadi alat yang efektif untuk memisahkan “kita” dan “mereka”, kawan dan lawan, sesuai dengan tujuan politik pragmatis masing-masing partisan.
Dengan argumen di atas, agama hanya bisa menjadi anugerah jika sekelompok orang/lembaga bisa menghindari upaya-upaya politisasi dan instrumentalisasi agama sesuai dengan kekuasaan dan kepentingan pragmatisnya. Sebab jika suatu lembaga keagamaan mempunyai tujuan kekuasaan yang pragmatis, maka akan mudah dan berani mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik yang mengatasnamakan “kebenaran” agamanya dengan cara yang mendukung kebijakan pemerintah tersebut.
Pada titik ini, legitimasi kebijakan pemerintah atas nama agama patut dipertanyakan. Jika kebijakan tersebut berupa pemberian izin pertambangan yang dalam praktiknya lebih banyak menimbulkan kerusakan ekologis, mengabaikan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial, maka terjadilah praktik perampasan kekuasaan yang sakral; Perampasan hak asasi manusia dan penyingkirannya dari ruang hidupnya sendiri atas nama kesucian (agama).
Kegiatan dan lembaga keagamaan tampaknya tidak lagi cukup hanya bertujuan memperkuat keimanan masyarakat kepada Tuhan atau hanya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Namun kita harus mempunyai keberanian politik untuk menolak praktik politisasi dan instrumentalisasi agama demi alasan pragmatis kekuasaan; Apalagi jika situasi ini menjadi kedok kapitalisasi sumber daya alam yang terbukti lebih parah dan membawa malapetaka bagi masyarakat. nasib manusia dan ruang hidupnya.
Karena mengingkari esensi agama yang sejak awal berdirinya menjadi sumber energi pembebasan kaum marginal, berwatak sosialis melawan eksploitasi dan akumulasi, serta membela prinsip keadilan dan kemanusiaan (Syed H Alatas, Islam dan Sosialisme ). , 2022). Oleh karena itu, penerapan agama bermuka dua harus menjadi cerminan penting apakah agama akan membawa berkah atau bencana tergantung bagaimana orang yang menganut agama tersebut berperilaku, bagaimana memahaminya, digunakan untuk apa, dan banyak orang. Lebih penting lagi, siapa yang akan kita bela?

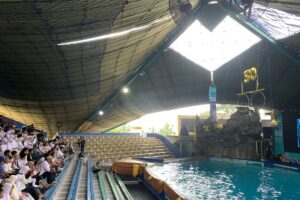


![[RE]Power Hackathon Ajang Inovator Muda Gagas Kebijakan Energi Bersih di Masa Depan](https://dlbrw.com/wp-content/uploads/2024/09/re-power-hackathon-ajang-inovator-muda-gagas-kebijakan-energi-bersih-di-masa-depan_5868798-300x200.jpg)














![[RE]Power Hackathon Ajang Inovator Muda Gagas Kebijakan Energi Bersih di Masa Depan](https://dlbrw.com/wp-content/uploads/2024/09/re-power-hackathon-ajang-inovator-muda-gagas-kebijakan-energi-bersih-di-masa-depan_5868798-768x511.jpg)



+ There are no comments
Add yours